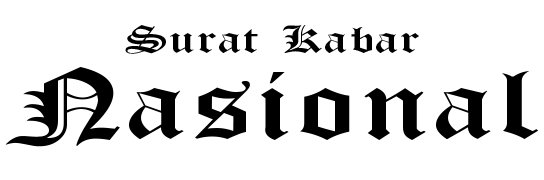JAKARTA – Unjuk rasa terbaru di Madagaskar kembali menyoroti keterlibatan China di seluruh Afrika, memunculkan pertanyaan-pertanyaan sulit tentang sifat pengaruhnya dan konsekuensi jangka panjang dari model pembangunan yang diterapkannya.
Mengutip dari PML Daily, Kamis (20/11/2025), hubungan China-Afrika yang dulu dipuji sebagai kemitraan saling menguntungkan, kini oleh banyak pihak dilihat sebagai relasi sarat ketimpangan, eksploitasi, serta meningkatnya rasa ketidaksukaan. Ibu kota Madagaskar, Antananarivo, menjadi pusat protes kekerasan pada Oktober 2025. Bisnis-bisnis milik investor China menjadi sasaran, sementara sejumlah distrik hancur berantakan.
Kekacauan ini terjadi setelah berminggu-minggu demonstrasi yang dipimpin kaum muda Gen Z terhadap pemadaman listrik berkepanjangan, kekurangan air, dan melonjaknya biaya hidup. Titik balik terjadi ketika frustrasi atas kegagalan tata kelola bersatu dengan kemarahan atas dominasi ekonomi asing, khususnya perusahaan China yang menguasai sejumlah sektor kunci perekonomian Madagaskar. Kisruh ini bukan kejadian tunggal.
Di berbagai negara Afrika, ketegangan serupa juga muncul. Di Zambia, para pekerja memprotes kondisi buruk di pabrik milik perusahaan China. Di Kenya, warga menuntut transparansi mengenai utang yang membengkak akibat proyek infrastruktur lewat skema Belt and Road Initiative (BRI). Di Nigeria, komunitas di sekitar area pertambangan melaporkan kerusakan lingkungan dan penggusuran. Rangkaian insiden ini mencerminkan kekecewaan yang semakin meluas terhadap BRI, yang dulu menjanjikan kesejahteraan tetapi kerap berujung ketergantungan dan ketimpangan.
Partai Komunis China (CCP) sejak lama menggambarkan kebijakan Afrika-nya sebagai model “kerja sama saling menguntungkan”. Namun para pengkritik menilai kenyataannya jauh lebih timpang. Perusahaan China, yang sering didukung pembiayaan negara dan pengaruh diplomatik, memperoleh kontrak dan konsesi lahan menguntungkan di seluruh Afrika. Di Madagaskar, mal dan toko impor yang dibiayai China mendominasi lanskap kota, sementara bisnis lokal berjuang untuk bertahan. Petani kehilangan tanah leluhur akibat proyek tambang, dan para nelayan mengaku hasil tangkapan menurun karena kapal asing beroperasi dekat garis pantai. Pendekatan CCP terhadap Afrika tampak didorong perhitungan strategis: mengamankan bahan baku, memperluas pengaruh geopolitik, dan menggalang dukungan diplomatik di forum internasional. Namun strategi ini semakin dikritik karena dianggap mengabaikan suara lokal dan melemahkan institusi demokratis. Di Madagaskar, para demonstran menyerukan pembongkaran struktur elitis, termasuk Senat dan mahkamah konstitusi, yang mereka nilai turut melanggengkan dominasi asing. Kehadiran China di Afrika bukan semata ekonomi, melainkan sangat politis. CCP menjalin hubungan erat dengan para elit berkuasa, sering kali di negara-negara dengan tata kelola lemah dan minim transparansi. Hal ini memunculkan tuduhan bahwa investasi China menopang rezim korup sambil mengabaikan kebutuhan warga. Di Madagaskar, monopoli layanan dasar oleh Jirama—perusahaan utilitas negara—dikaitkan dengan salah kelola dan praktik kronisme, yang memperburuk kemarahan publik.
Narasi CCP tentang pembangunan yang penuh niat baik semakin diragukan oleh laporan pelanggaran tenaga kerja dan diskriminasi rasial. Video viral dari lokasi konstruksi memperlihatkan mandor China memarahi pekerja Afrika, memperkuat persepsi kesombongan neo-kolonial. Insiden-insiden seperti ini memicu rasa tersinggung yang kian kuat. “Mengapa kami diatur-atur di tanah kami sendiri?” tanya seorang pekerja lokal, mewakili sentimen yang bergema di seluruh benua.
Dampak dari krisis Madagaskar dapat menjadi titik balik hubungan Afrika–China. Ketika protes menjalar ke kota-kota seperti Toamasina dan Mahajanga, dan kedutaan-kedutaan asing menyerukan dialog damai, pertanyaan soal kepercayaan pun mengemuka. Mampukah China menyesuaikan pendekatannya untuk mengutamakan martabat, keadilan, dan kemitraan sejati? Atau apakah batas telah terlampaui sehingga rasa ketidaksukaan kini lebih besar dari niat baik?
Respons CCP dapat diprediksi: menuduh kerusuhan sebagai ulah kelompok ekstremis. Namun bantahan semacam itu mengabaikan masalah struktural yang menjadi akar kemarahan. Ketika manfaat pembangunan hanya dirasakan segelintir elite dan meninggalkan mayoritas, ketidakstabilan menjadi konsekuensi yang tak terhindarkan. Peristiwa di Madagaskar bukan sekadar krisis nasional, melainkan cermin yang memantulkan kegagalan lebih luas dari strategi keterlibatan China di Global South.
Afrika tidak lagi ingin menjadi penerima pasif bantuan asing. Generasi baru aktivis, pengusaha, dan pemimpin masyarakat sipil menuntut akuntabilitas, transparansi, dan penghormatan. Mereka mengajukan pertanyaan-pertanyaan mendasar: siapa yang mengendalikan pelabuhan, tambang, dan lahan pertanian? Siapa yang menikmati keuntungan dari ledakan proyek infrastruktur? Dan jika pembangunan berarti mengorbankan kedaulatan serta martabat, apakah itu benar-benar kemajuan? CCP harus menjawab pertanyaan-pertanyaan ini dengan kerendahan hati. Impiannya tentang Belt and Road Initiative yang terpadu dapat runtuh jika dibangun di atas keheningan mereka yang diklaim ingin dibantu. “Kami bukan budak. Kami hanya ingin hidup dengan martabat,” seru seorang demonstran di Madagaskar. Seruan itu, yang menggema di berbagai penjuru Afrika, adalah panggilan untuk menciptakan bentuk kemitraan baru yang berlandaskan empati, bukan eksploitasi.